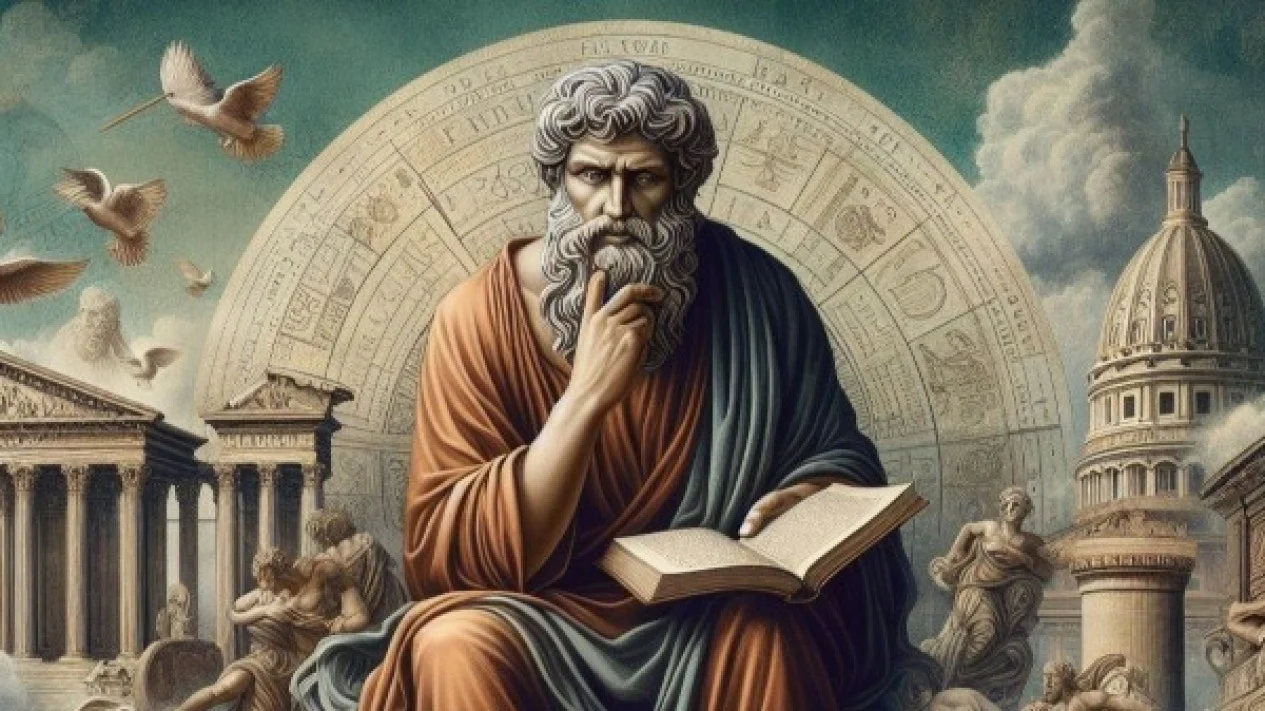Dalam sejarah peradaban manusia, kudeta menjadi salah satu bentuk peralihan kekuasaan yang kerap kali diwarnai oleh kekerasan, pengkhianatan, dan instabilitas. Secara sederhana, kudeta dapat dimaknai sebagai penggulingan kekuasaan yang sah oleh kelompok tertentu secara paksa dan ilegal. Peristiwa semacam ini menimbulkan perdebatan panjang di kalangan filsuf politik. Beberapa pandangan filosofis memandang kudeta dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, sementara lainnya menganggapnya sebagai pelanggaran moral dan ancaman terhadap tatanan sosial.
Dari perspektif kontrak sosial, John Locke menyatakan bahwa kekuasaan politik yang sah berasal dari persetujuan rakyat. Bila pemerintah menyalahgunakan wewenangnya, mengabaikan hak-hak dasar rakyat, serta gagal melindungi kehidupan, kebebasan, dan hak milik, rakyat berhak melakukan perlawanan, termasuk menggulingkan kekuasaan tersebut. Bagi Locke, kudeta bukan sekadar pemberontakan, melainkan tindakan etis untuk memulihkan keadilan dan kedaulatan rakyat.
Senada dengan Locke, Jean-Jacques Rousseau dalam gagasan kehendak umum (volonté générale) berpendapat bahwa kekuasaan sah hanyalah yang berjalan selaras dengan aspirasi rakyat. Jika kekuasaan menyimpang dari kontrak sosial dan menindas rakyat, maka kudeta menjadi cara untuk merebut kembali kedaulatan itu. Bahkan dalam konteks utilitarianisme, Jeremy Bentham dan John Stuart Mill memandang tindakan politik, termasuk kudeta, harus diukur dari manfaatnya bagi kebahagiaan bersama. Jika kudeta membawa kemaslahatan lebih besar ketimbang kerugian, maka secara moral dapat diterima.
Namun, penolakan terhadap kudeta datang dari pandangan filsafat hukum positif, seperti yang diajukan oleh Thomas Hobbes. Ia meyakini bahwa ketertiban sosial hanya dapat terjaga melalui otoritas absolut. Kudeta, baginya, merupakan ancaman bagi stabilitas dan berpotensi menjerumuskan masyarakat dalam situasi anarki, di mana hukum rimba berlaku. Demikian pula Hans Kelsen yang menegaskan bahwa negara modern harus berjalan berdasarkan norma hukum, bukan kekuasaan senjata. Kudeta hanya akan merusak legitimasi sistem hukum dan membuka celah kekuasaan tanpa dasar legal.
Dari sudut pandang etika deontologi, Immanuel Kant menilai tindakan bukan dari akibatnya, melainkan dari prinsip moralnya. Kudeta, sekalipun dimaksudkan untuk kebaikan, tetap tidak dapat dibenarkan bila didasarkan pada niat yang salah dan metode yang melanggar nilai moral, seperti kekerasan dan pengkhianatan terhadap aturan yang sah.
Kesimpulannya, landasan filosofis tentang kudeta terbelah ke dalam dua kutub. Di satu sisi, kudeta dapat dibenarkan bila bertujuan untuk menumbangkan kekuasaan tiran dan memulihkan keadilan bagi rakyat. Di sisi lain, kudeta dinilai berbahaya karena merusak tatanan hukum, mengancam ketertiban sosial, dan bertentangan dengan prinsip moral universal. Perdebatan ini menunjukkan bahwa politik selalu bergerak dalam ruang abu-abu antara legitimasi moral dan legalitas hukum.